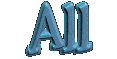| Dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh.
Sungguh Tuhanku benar-benar Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang (QS. Huud 11:41)
Dan luka selalu menyimpan sesuatu yang menyesakkan jiwa. Raida, ibu muda beranak satu, mengeluhkan ihwal itu di suatu sore.
“Wah, saya jadi ngeri naik kapal dan pesawat. Bahkan naik bus sekalipun. Saya jadi trauma. Apalagi melihat kecelakaan pesawat dan kapal laut yang banyak memakan korban, saya tambah malas untuk bepergian. Kalau bisa saya tidak ingin kemana-mana. Saya sudah pusing, saya mau di rumah saja.”
“Kenapa bisa begitu bu?”
“Saya pernah mengalami kecelakaan bis yang cukup serius. Alhamdulillah, hampir semua penumpang selamat. Hanya dua orang yang meninggal. Tapi saya dan penumpang lainnya rata-rata terluka. Waktu itu, saya sendiri mengalami cedera dan patah tulang agak serius. Yang membuat saya trauma; teriakan histeris para penumpang, detik-detik menakutkan sebelum terjadi tabrakan…ihh… mengerikan.”
Kisah Bu Raida pun berhenti di kata ‘mengerikan’ itu. Sejenak saya terhenyak. Tercenung, merenung: Bagaimana dengan mereka yang selamat dari Adam Air? Bagaimana dengan mereka yang lolos dari KM Levina? Adakah kata ‘mengerikan’ terasa cukup mewakili luka itu, rasa maut di ujung tanduk itu?
Inilah sebuah kondisi ketika luka meninggalkan ceruk-ceruk gulita di benak mereka yang lolos dari pelbagai musibah itu; luka yang belum sembuh selepas tragedi tragis itu, luka yang terus menyesakkan jiwa. Dan kita biasa menyebutnya itulah trauma! Dan Bu Raida, hanyalah secuil kisah pedih mengenainya. Namun, bagaimanakah bila di setiap orang yang trauma memiliki kesimpulan yang serupa Bu Raida; menjadi malas untuk bergerak, bepergian dan melakukan perjalanan?
Nah, bila maut yang menjadi sumber kecemasan. Bu Raida dan orang yang senasib dengannya, maka bukankah maut tidak pernah memilih ruang dan waktu? Kapanpun, dimanapun ia bebas memilih. Tapi, jika maut bukan pangkal soalnya, melainkan perkara bagaimana maut menjemput Bu Raida, atau ihwal ketakutan-ketakutan yang membayangi Bu Raida selama berada dalam perjalanan, saya jadi teringat peribahasa Cina yang berbunyi, “Perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah pertama.”
Kenapa? Sebab, langkah pertamalah yang menentukan keberlanjutan kisah perjalanan kita. Ia, pada hakikatnya, serupaniat. Bisa juga kita sebut visi. Atau apalah namanya yang membuat kita untuk memutuskan untuk mengadakan perjalanan entah kemana. Yang jelas, di titik inilah, sebetulnya, kita menghimpun tujuan dan harapan. Bolehlah ia kita sebut sebagai starting point penentu keberhasilan perjalanan kita.
Lalu, bagaimanakah langkah pertama perjalanan kita seharusnya dimulai?
Di sinilah, saya teringat doa yang pernah dibaca Nabi Nuh as. Di atas. Semoga saja anda, terutama mereka yang pernah mengenyam dunia pesantren, masih mengingat kisah terbitnya doa tersebut. Kendati demikia, bila memori anda telah berkarat, seperti saya, mari kita ingat kembali potongan kisah itu:
Syahdan, ketika mayoritas penduduk negeri Armenia membantah seruan kebajikan Nuh as., sebuah titah Allah –melalui malaikat jibril- turun menyapanya: “wahai Nuh, tanamlah benih pohon dari surga ini.” Nuh –yang selama ini telah 950 tahun berdakwah di hadapan mereka- bersegera menanamnya. Dalam beberapa tahun, pohon itupun tumbuh dan berkembang menjulang begitu tinggi. Ajaibnya, sejak pohon itu dibenamkan ke bumi hingga tumbuh besar; tak ada satupun bayi yang lahir. Setelah itu, jibril kembali menghampiri Nuh untuk menyampaikan wahyu Allah bahwa pohon itu harus segera ditebang dan dibuat bahtera.
Kontan saja, perintah Allah yang satu ini menjadi bahan cemoohan penduduk Armenia yang kafir. Pasalnya negeri dimana mereka tinggal adalah dataran tandus. Musim penghujan pun belum datang. Untuk apa bahtera besar yang tengah digarap Nuh dan pengikutnya itu? Dan Allah memang punya rencana. Dia, Pemilik Sang Maha, tiba-tiba mengirim risalah wahyu untuk sang nabi, “Wahai Nuh, segeralah berkemas! Himpunlah orang-orang yang beriman yang menjadi pengikutmu! Jangan lupa hewan-hewan jantan dan betina!”
Wahyu itu menyebar begitu cepat. Semua yang beriman sibuk. Semua berkemas. Semua bergegas. Dan, ketika bahtera itu memuat Nuh dan pengikutnya dan hewan-hewannya, dan barang-barangnya, tiba-tiba langit berubah kelam. Awan tebal memanyungi bumi. Dan hujan dahsyat pun turun menggenangi tempat mereka berpijak. Bukan hanya hujan, segenap mata air pun memancar. Tak ayal air bah pun melanda negeri, menyapu desa, melahap kota. Saat itulah, perahu yang dibuat Nuh dan pengikutnya mulai bergerak. Pada momen inilah, Nuh berkata: “Bismillahi majraahaa wa mursahaa inna rabbi laghafuur rahiim.”
Di mata alim Thabathaba’i, lafal Basmallah yang dibaca Nuh adalah sebuah asa agar senarai kebajikan dan keberkahan senantiasa menyertai perjalanan bahtera mereka, terhitung sejak mereka bertolak dan berlabuh.
Yah, pada akhirnya langkah pertama pengembaraan kita itu memang Basmalah sebagaimana yang dicontohkan Nuh. Pada kata inilah, ketika kita mulai menjejakkan langkah kali pertama di atas satu kendaraan, kita seharusnya dapat membebaskan diri dari kelebat risau, cekam, dan trauma yang nyeri, ia menjadi tempat untuk merenung kembali niat perjalanan kita; apakah untuk tujuan yang baik atau malah sebaliknya?
Kata inipun seyogyanya menjadi suluh bagi relung batin kita agar gelisah dan gundah yang kita khawatirkan itu menghilang selama kita menempuh perjalanan. Bayangkanlah, ketika doa Nuh ini kita panjatkan, kita tengah bepergian bersama Allah, kita tengah mempersilahkan segenap pasrah pada Sang Kholik yang meulurh di jiwa kita. Dan bila kemungkinan terburuk itu terjadi, saya yakin Allah Maha baik untuk memberi ganjaran kepada hamba-Nya yang kerap mendzikir namaNya di setiap detik hidupnya.
Dalam pada itu, tak salah bila Thabathaba’i selanjutnya menegaskan, “Mengaitkan satu pekerjaan atau persoalan dengan nama Allah swt, merupakan cara untuk memeliharanya dari kehancuran, kebinasaan, kerusakan, kesesatan, dan kerugian. Kenapa? Karena Allah swt adalah Yang Maha Tinggi dan Maha Kuat yang tak bisa disentuh oleh kebinasaan, kefanaan, dan kelemahan, sehingga apa yang berkaitan dengan-Nya tidak akan tersentuh oleh keburukan.”
Bagi saya pribadi, terlepas dari doa Nuh yang kita baca, yang layak kita cermati juga adalah perjalanan kita sendiri. Ini bukan lagi perkara kendaraan apa yang kita gunakan selama bepergian, tapi soal bagaimanakah sebetulnya kita memknai setiap perjalanan itu sendiri?
Setiap Kita Adalah Seorang Musafir
Dan hidup adalah sebuah perjalanan, sebuah pengembaraan. Kita, pada hakikatnya, bukan seorang pemukim, yang menetap dan bercita-cita tidak ingin berhijrah serta melanglang kemana-mana. Kita selayaknya menjadi sang pengelana, seorang pejalan yang terus menerus berstatus musafir.
Bukankah Nabi Muhammad saw suatu kali pernah mengabarkan perkara ini? Sabdanya. “Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti seorang musafir.”
Dalam pada itu, ihwal hadis ini para ulama menafsirkannya seperti ini “janganlah engkau condong kepada dunia, janganlah engkau menjadikannya sebagai tempat tinggal abadi; janganlah terbetik dalam hatimu untuk tinggal lama padanya; dan janganlah engkau terikat dengannya kecuali sebagaimana terikatnya orang asing di negeri perantauannya, sebab orang asing sejatinya tidak akan terikat di negeri kelananya kecuali sedikit sekali dari sesuatu yang dia butuhkan.”
Sebagai mukmin, bila merujuk wasiat Nabi dia tas, setiap kita adalah seorang musafir, seorang yang melakukan perjalanan demi menunaikan tugas suci Sang Tuan, Allah Azza wa jalla. Karena itu siapakah diantara kita yang berhasil menjadi hamba yang paling bagus mengemban amanah-Nya? (Ya Allah, semoga kami, hamba-hamba-Mu yang dhoif termasuk musafir yang berhasil).
Pesan rasulullah inilah yang kian meyakinkan saya bahwa di setiap safar (perjalanan) kita, kemanapun kita pergi, kendaraan apapun yang kita gunakan adalah ruang menguji jiwa kita. Di setiap rangkaian safar, kita kerap kali menjumpai beragam lapis masyarakat; pelbagai suasana hati yang tak menentu; pikiran-pikiran yang kadang lurus, kadang juga berkelok-kelok.
Pada rupa-rupa pengalaman itulah, kita menyerap makna dan sejumlah hikmah. Kita menyimpan segenap suka dan duka sebagai bekal kenangan ketika pulang ke rumah-Nya, sebagai modal cerita ketika tetitah di rumah-Nya, sebagai pertanggungjawaban yang akan dituntut Sang Pemilik Rumah, Allah Azza wa jalla. Maka Sang rahman pun berkata, “Inna ilaina iyabahum, tsumma ina’alaina hisabahum, Kepada Kami-lah mereka kembali, kewajiban Kami-lah untuk memeriksa mereka semua,” (QS. Al-Ghaasyiyah: 25-26). Wajar bila Imam Ghozali dalam Kimiya yi sa’adat (Alchemy of Happiness) menuturkan bahwa: “Kunci untuk memahami diri adalah hati-bukan hati secara fisik melainkan hati yang diberikan Tuhan kepada kita, yang datang ke dunia sebagai pengelana mengunjungi negeri asing dan segera kembali ke negeri asalnya.”
Akhir kalam, saya kira, Bu Raida dan teman-teman senasib dengannya atau kita sendiri memang perlu menghidmati bahwa-meski tidak berniat mengadakan perjalanan kemana-mana (atau memilih berdiam di suatu tempat) lantaran trauma atu hal lainnya- sejatinya, kita pun tengah bersafar; kita tengah di negeri rantau. Dengan sikap inilah, doa Nuh yang kita lafalkan akan terasa menjadi safar yang terindah, safar yang juga bernilai ibadah. firlianaputri (at) yahoo dot com ( DUDUNG>NET) 
|